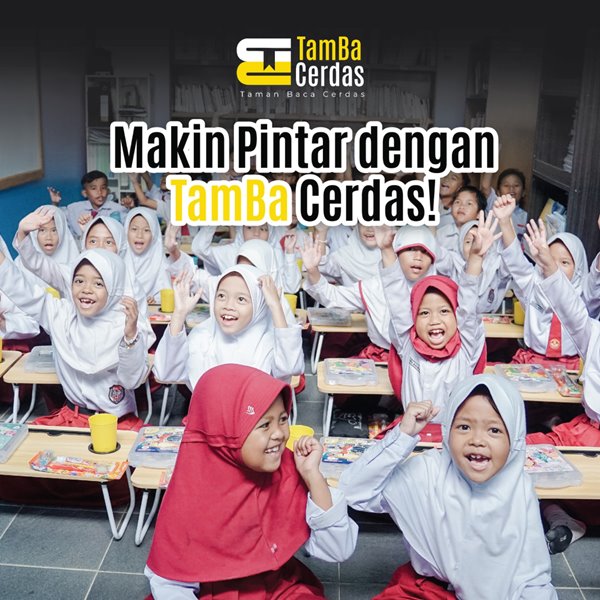Kenali Profil Ki Hadjar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional
Ki Hadjar Dewantara adalah sosok visioner dalam sejarah pendidikan Indonesia. Lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat, ia sebenarnya berasal dari kalangan bangsawan Kesultanan Pakualaman. Namun, beliau memilih untuk menyatu dengan rakyat jelata yang kala itu nyaris tak tersentuh akses pendidikan.
Dikenal sebagai Bapak Pendidikan Nasional, Ki Hadjar Dewantara tak hanya membangun institusi, tetapi juga merancang filosofi pendidikan yang menyentuh akar budaya bangsa. Pada 3 Juli 1922, ia mendirikan Taman Siswa yang merupakan sebuah lembaga pendidikan yang membuka akses belajar bagi rakyat biasa yang selama ini termarjinalkan oleh sistem kolonial.
Di sanalah lahir semboyan Ki Hadjar Dewantara yang masyhur: “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani.” Inilah cikal bakal filosofi pendidikan Indonesia yang menempatkan guru sebagai teladan, penggerak, sekaligus pembimbing. Hingga hari ini, arti Tut Wuri Handayani tetap hidup dalam setiap proses pendidikan di tanah air.
Sebagai penghormatan atas jasa-jasanya, pemerintah menetapkan tanggal lahirnya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Pada 28 November 1959, ia resmi dinobatkan sebagai Pahlawan Nasional. Dedikasinya menciptakan sistem pendidikan inklusif dan berkarakter menjadi warisan abadi bagi bangsa ini.
Perjalanan Pendidikan yang Membentuk Pandangan
Ki Hadjar Dewantara menempuh pendidikan formal pertamanya di Europeesche Lagere School (ELS), sebuah sekolah dasar khusus anak-anak Eropa dan bangsawan. Kesempatan ini ia peroleh karena status keluarganya sebagai bangsawan Pakualaman.
Meski mendapat hak istimewa, justru dari sana ia melihat ketimpangan akses pendidikan antara kaum elit dan rakyat jelata. Kesadaran ini menjadi bibit dari idealisme pendidikan yang kelak ia perjuangkan.
Setelah ELS, ia melanjutkan ke Kweekschool di Yogyakarta. Selanjutnya, ia menempuh pendidikan di STOVIA (School tot Opleiding van Inlandsche Artsen), sebuah sekolah kedokteran bagi pribumi di Batavia. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikan di sana karena kondisi kesehatan. Masa-masa tersebut memperkaya cara pandangnya tentang pentingnya pengetahuan dan pembentukan karakter bangsa melalui pendidikan.
Keterbatasan formalitas akademik tak menghalangi Soewardi muda menjadi pemikir dan penulis tajam. Pendidikan, bagi Ki Hadjar Dewantara, bukan sekadar pengetahuan teoritik. Ia melihatnya sebagai proses pembebasan, pemberdayaan, dan pembentukan identitas bangsa.
Pemikirannya juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh besar dunia seperti Rabindranath Tagore dari India dan Maria Montessori dari Italia. Dari Tagore, ia menyerap konsep pendidikan yang membebaskan dan menumbuhkan cinta tanah air. Dari Montessori, ia belajar pentingnya lingkungan belajar yang menyenangkan dan menghargai perkembangan anak. Inilah fondasi yang kelak membentuk sistem Among dalam Taman Siswa.
Dari Jurnalis Menjadi Aktivis Pergerakan
Sebelum dikenal sebagai tokoh pendidikan, Ki Hadjar Dewantara mengawali karier sebagai jurnalis di berbagai surat kabar. Ia dikenal tajam dan berani dalam menyampaikan kritik terhadap pemerintah kolonial Belanda.
Ia menyuarakan keresahan sosial dan ketidakadilan kolonial melalui tulisan-tulisan yang tajam namun elegan. Aktivitas intelektual inilah yang mempertemukannya dengan berbagai tokoh pergerakan.
Bersama Douwes Dekker dan Tjipto Mangunkusumo, ia mendirikan Indische Partij yang menjadi organisasi nasionalis pertama yang secara tegas menyerukan kemerdekaan Indonesia. Mereka dikenal sebagai Tiga Serangkai, simbol awal perlawanan intelektual terhadap kolonialisme.
Setelah dibubarkannya Indische Partij, Ki Hadjar ikut mendirikan Komite Boemipoetra untuk terus mengkritik penjajahan lewat tulisan dan pergerakan. Tulisannya yang berjudul “Als Ik Eens Nederlander Was” (Seandainya Aku Seorang Belanda) menjadi pemicu pembuangan dirinya ke Belanda pada 1913.
Di pengasingan, ia justru memperluas wawasan pendidikan dan filsafat kebangsaan. Ia banyak belajar dari pemikiran tokoh dunia seperti Maria Montessori dan Rabindranath Tagore. Gagasan pendidikan yang membebaskan mulai ia rumuskan selama masa pengasingan, sebagai bekal membangun sistem pendidikan pribumi sepulang ke tanah air.
Kembali ke Indonesia pada 1919, Ki Hadjar Dewantara semakin mantap menjadikan pendidikan sebagai medan perjuangan. Ia sadar bahwa kebodohan adalah alat kolonialisme, dan pendidikan menjadi sarana utama untuk membebaskan rakyat. Langkahnya pun beralih dari tulisan menuju gerakan pendidikan sistemik.
Jurnalistik telah membentuk keberanian berpikirnya, tetapi dunia pendidikan memberi ruang untuk menciptakan perubahan berkelanjutan. Di sinilah arah hidupnya berubah, dari juru bicara perlawanan menjadi pelopor pendidikan nasional yang revolusioner.
Mendirikan Taman Siswa: Pendidikan untuk Rakyat
Pada 3 Juli 1922, Ki Hadjar Dewantara mendirikan Onderwijs Instituut Taman Siswa di Yogyakarta. Lembaga ini hadir sebagai alternatif dari sistem pendidikan kolonial yang eksklusif. Di Taman Siswa, rakyat jelata mendapat kesempatan belajar dengan pendekatan yang membebaskan untuk menggali potensi masing-masing siswa.
Taman Siswa tidak hanya memberi akses pendidikan, tetapi juga menanamkan karakter nasionalisme dan kebudayaan. Sistemnya menggabungkan nilai tradisional Jawa dan modernitas Eropa. Ini menjadikan pendidikan sebagai proses pembentukan manusia merdeka secara utuh, secara jasmani, rohani, dan sosial.
Sebagai bentuk keberpihakannya pada rakyat, ia mengganti namanya menjadi Ki Hadjar Dewantara dan menanggalkan gelar kebangsawanannya. Ia ingin menjadi pendidik yang membaur dan mengabdi tanpa sekat sosial. Ini menjadi sebuah tindakan simbolik yang sangat bermakna pada masa itu.
Di Taman Siswa, ia mengembangkan sistem Among, di mana guru bukan penguasa, melainkan pembimbing yang membebaskan murid. Tidak ada paksaan, tidak ada hukuman, dan tidak ada tekanan. Pendidikan dilakukan dengan kasih sayang untuk menumbuhkan minat belajar secara alami.
Salah satu warisan terbesarnya adalah semboyan Ki Hadjar Dewantara: “Ing ngarsa sung tuladha, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani”. Arti Tut Wuri Handayani yakni memberi dorongan dari belakang. Ini menjadi filosofi pendidikan Indonesia hingga hari ini.
Warisan dan Pengaruh dalam Sistem Pendidikan Nasional
Konsep pendidikan yang dikembangkan Ki Hadjar Dewantara sangat berpengaruh terhadap arah sistem pendidikan nasional. Ia meletakkan fondasi bahwa pendidikan harus menumbuhkan budi pekerti, bukan sekadar kecerdasan intelektual. Pendidikan bukan alat kekuasaan, melainkan jalan pembebasan.
Setelah Indonesia merdeka, Ki Hadjar Dewantara diangkat sebagai Menteri Pengajaran (kini Menteri Pendidikan) pada kabinet pertama Republik Indonesia. Dalam jabatan tersebut, ia merumuskan dasar sistem pendidikan nasional yang berjiwa kebangsaan, demokratis, dan berbasis kebudayaan.
Meski zaman telah berubah, prinsip pendidikan yang dicetuskan Ki Hadjar Dewantara tetap relevan. Gagasan tentang pendidikan yang memerdekakan individu kini sejalan dengan pendekatan pedagogi modern, bahkan mirip dengan sistem pendidikan di negara maju seperti Finlandia.
Ia juga menyadarkan bahwa pendidikan bukan semata-mata tanggung jawab negara, melainkan gerakan masyarakat. Filosofi inilah yang membuat Taman Siswa terus hidup, meski menghadapi tekanan politik dan kebijakan kolonial seperti Ordonansi Sekolah Liar.
Ki Hadjar Dewantara wafat pada 26 April 1959 dan dimakamkan di kompleks pemakaman keluarga Taman Siswa Wijayabrata, Yogyakarta. Namun gagasannya tetap hidup, mengalir dalam semangat setiap pendidik dan pelajar Indonesia yang percaya bahwa pendidikan adalah jalan menuju kemerdekaan sejati.
Bisa dibilang, Ki Hadjar Dewantara bukan hanya pendidik, tetapi juga arsitek peradaban. Ia menggabungkan pemikiran modern dengan nilai-nilai lokal. Ia menghidupkan kembali budaya bangsa dalam bingkai pendidikan dan menawarkan jalan revolusioner melalui cara yang menggugah. Inilah contoh bagaimana pendidikan bukan sekadar transmisi ilmu, melainkan proses pembebasan dan penciptaan manusia merdeka.